
Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism(1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.
Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.
Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.
Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa – dalam keanekaragaman – ini tetap memiliki keinginan hidup bersama – dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?
Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.
Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.
Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.
Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.
Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.
Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.
Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.
Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.
Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.
Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.
Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.
Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.
Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.
Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?
Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.
Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.
Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.
Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.
Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.
Thomas Koten, Direktur Social Developoment Center.
Artikel ini telah diterbitkan di sinar harapan pada 14 Agustus 2014.
Foto: Tribunnews

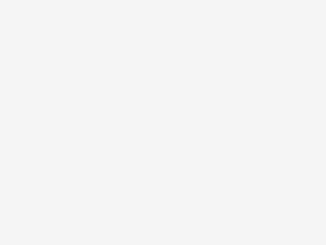

Be the first to comment