
Ada perbedaan di Indonesia. Itulah titik berangkat kita. Ada perbedaan yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, dan bertumpang-tindih. Perbedaan agama, aliran-aliran di dalam satu agama, sukubangsa, ideologi, bahasa, partai, selera, pendidikan, dll, mewujud dalam perbedaan pandangan, sikap, perilaku, kebiasaan, pilihan, dst.
Tanggapan terhadap perbedaan pun berbeda-beda. Ada orang yang sangat senang perbedaan. Mereka dengan semangat mencari tahu segala hal yang berbeda; mereka belajar, mereka menikmati, mereka gembira akan segala hal baru dan lama yang berbeda dengan keadaan dan pandangan diri mereka sendiri. Mereka bergaul dan berbaur saling cinta saling jaga. Tidak ada ketidaksetujuan di sini. Karena itu, tidak ada tolerasi. Dengan demikian, tidak ada toleransi.
Banyak kata bisa dipakai untuk keadaan ini—harmoni, serasi, selaras, indah, pluralis, majemuk, ideal, sejuk, gotong-royong, solidaritas, dll. Banyak kata yang masing-masing bisa menggambarkan dengan tepat keseluruhan atau aspek tertentu keadaan dan sikap yang sangat surgawi ini. Tapi toleransi bukan salah satunya. Tidak ada dan tidak perlu ada toleransi di surga.
Ada orang yang tidak senang perbedaan. Mereka tidak setuju perbedaan. Mereka mengambil sikap menentang secara aktif. Mereka bukan hanya tidak setuju. Mereka menolak dan berusaha menghambat atau melarang pandangan, sikap, dan atau perbuatan yang tidak mereka setujui itu. Dalam bahasa generasi lalu, mereka tidak mentolerir hal yang tidak mereka setujui. Mereka menggunakan tekanan psikologis, kekuatan massal, serangan ideologis, kekuasaan negara, ancaman hukum, ketajaman golok, dan hantaman pentung untuk berusaha menghancurkan dan melenyapkan orang dan pihak yang berbeda dari mereka. Mereka menciptakan neraka bagi orang-orang yang mereka musuhi agar takut dan lari pergi, atau mati. Kenegatifan ini bisa disebut pertentangan, permusuhan, intoleransi, disharmoni, kebencian, kepicikan, kesempitan, keganasan, atau apa saja yang bermakna serupa. Yang jelas bukan toleransi. Tidak ada toleransi di neraka.
Ada orang yang tidak setuju pada perbedaan tertentu. Tapi mereka yang tidak setuju ini tidak melakukan sesuatu terhadap orang yang tidak mereka setujui. Mereka diam saja, tidak menentang secara fisik orang yang pendapat atau perilakunya tidak mereka setujui. Mereka mengambil sikap kurang lebih: hidupmu hidupmu, hidupku hidupku. Mereka tidak berusaha membungkam atau mencengkam orang atau pihak yang tidak mereka sukai. Sebagian tidak hanya diam, tapi secara aktif berdebat, bersilat lidah, secara langsung pribadi atau melalui media umum. Mereka berbicara, atau mengecam dan menyalahkan, tapi mereka tidak mementung atau membacok, tidak memenjarakan atau mengusir. Inilah tolerasi. Tidak setuju, tapi tidak berbuat sesuatu yang negatif terhadap persona orang yang tidak disetujui atau disukai. Ini belum toleransi. Dekat, tapi belum. Mirip, tapi bukan.
Dari orang-orang yang bertolerasi ini, sebagian akan tetap diam saja ketika orang atau pihak yang tidak mereka setujui itu mengalami perlakuan tidak adil dari orang atau pihak yang berusaha memburuki atau menggebuki mereka. Walaupun mereka bertolerasi terhadap orang yang tidak mereka setujui tindakan, perilaku, atau pandangannya, mereka tidak berusaha membela ketika orang-orang itu, dalam kedudukan lemah, dicederai dan dicelakai, ditindas dan ditikam oleh orang yang tidak bertolerasi, atau oleh negara dan atau aparatur negara. Mereka bertolerasi, tapi tidak bertoleransi.
Sebagian orang yang bertolerasi mengambil sikap aktif membela hak-hak orang atau pihak yang tidak mereka setujui. Mereka memakai prinsip Voltaire yang sering dikutip itu. Walaupun bukan langsung dari pena atau mulutnya, melainkan dari parafrase penulis biografinya, Evelyn Beatrice Hall, kutipan itu adalah intisari toleransi dalam pemikiran filsuf utama Prancis itu: “Aku tidak setuju apa yang kamu katakan, tapi aku akan membela mati-matian hakmu untuk mengatakannya”.
Seorang yang bertoleransi adalah seorang yang, ketika masyarakat berada dalam keadaan tenang, membiarkan segala macam pandangan dan perilaku yang tidak dia setujui – yang dikemukakan oleh segala macam orang di segala bidang kehidupan – tetap berkumandang dan berkembang; atau mereka secara aktif terlibat dalam perdebatan dengan kata-kata dan bertikai hanya secara rasional dengan mereka yang berbeda pandangan itu.
Seorang yang bertoleransi adalah seorang yang, ketika masyarakat berada dalam keadaan tegang, menggunakan segala kemampuan, segenap kekuatan, dan sepuncak kecerdasannya untuk membela dan memperjuangkan hak orang dan pihak yang tidak mereka setujui itu untuk melanjutkan tindakan dan memperluas pandangan mereka dengan leluasa.
Orang yang bertoleransi akan berkata, aku tidak setuju pendapatmu, kalau bisa aku harap kamu mengubah sikap dan pandanganmu. Aku bahkan akan berusaha membujuk dan meyakinkanmu dengan damai untuk menganut pendirianku. Tapi aku tidak akan memaksa kamu dengan kekerasan atau dengan hukum atau dengan kekuatan negara sehingga kamu menjadi takut dan tunduk kepadaku. Kuhargai hakmu untuk berpegang pada keyakinanmu dan perilakumu. Dan kalau ada orang lain berusaha menganiaya dan menindasmu karena keyakinanmu itu, apabila ada orang berusaha menjahati dan menzalimi kamu karena pandanganmu dan perilakumu itu, aku akan membelamu dan memperjuangkan hakmu dengan sekuat tenagaku.
Orang Indonesia secara tradisional tidak mengenal toleransi atau tolerasi, melainkan harmoni. Kehidupan tradisional ideal yang aman tenteram adalah kehidupan selaras serasi. Perbedaan dikurangi. Perasaan tidak suka dipendam. Perselisihan diredam. Kebencian tak punya wajah. “Ya” adalah jawaban paling indah di telinga semua orang. Setuju dan sepakat adalah cita-cita sosial yang dijunjung tinggi. Selaras seperti dawai-dawai yang dikencangkan dengan sempurna tegangannya sehingga menimbulkan ragam bunyi yang nyaman di telinga. Serasi seperti gugus-gugus bintang di langit yang berbaris setiap malam tanpa pernah terlihat melanggar jalan dan jalur tetangganya. Begitulah ideal kehidupan sosial masyarakat tradisional Indonesia pada umumnya.
Tapi orang Indonesia masa kini tidak hidup dalam dunia tradisional. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, pola kehidupan masyarakat tradisional hanya bisa dijaga dan diselamatkan unsur-unsur tertentunya saja, tidak bisa dipertahankan seutuhnya. Keluarga perdesaan Jawa mungkin masih bisa mengandalkan tetangga dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, tapi di kota-kota rukun tetangga dan rukun warga memiliki sifat dan fungsi berbeda. Keluarga Padang di rantau harus berinovasi dalam melanjutkan tradisi pewarisan harta pusaka matriarkat. Demikianlah perubahan dan penyesuaian harus dialami dan dijalani semua dan setiap masyarakat Indonesia yang membuka diri terhadap kehidupan modern dan pengaruh nasional dan global.
Harmoni, ketika semua dan setiap orang sepakat sehasrat dan sehati sejiwa tidak bisa lagi menjadi cita-cita kebersamaan masyarakat kontemporer Indonesia. Toleransi, ketika pertikaian dan perselisihan adalah kebiasaan normal yang berlangsung dalam damai dan penuh akal budi dengan sikap saling hormat dan saling junjung martabat, ketika perbedaan pandangan dan perilaku justru menghasilkan adu otak dan asah jiwa yang menjadi motor kemajuan dan perbaikan, adalah ideal maksimal suatu masyarakat modern yang merdeka sebagai satu bangsa, merdeka sebagai kelompok-kelompok manusia, dan merdeka sebagai seorang-seorang.
Penulis adalah pengamat bahasa dan sosial, tinggal di Jakarta
Tulisan ini telah dimuat di sinarharapan.com pada 24 November 2014.


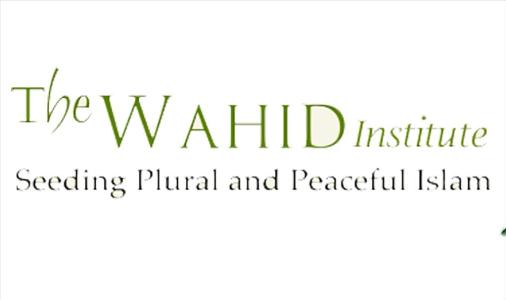

Be the first to comment